Merupakan lanjutan dari bagian pertama yang mengupas tentang Binongko dan Tomia. Di sesi ke dua ini membahas tentang Kaledupa dan Wangi-Wangi.
Pulau Subur Bernama Kaledupa
Saya beralih makin ke utara, Pulau Kaledupa lebih berbukit dan subur. Tanaman dan pohon tinggi mudah dijumpai. Rasanya tak seperti di dataran rendah. Mungkin ini yang menjadikan Kaledupa sebagai pusat peradaban Wakatobi di masa lalu saat bernama Barata Kahedupa yang termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Tak heran pula hampir semua rumah-rumah di sini masih mengikuti tradisi dengan bentuk panggung.
“Adat dan budaya di sini relatif lebih kental. Nilai-nilai tradisional masih cukup kuat”, kata La Bloro ketua Forkani salah satu LSM di Kaledupa. Saya menemui pria berkacamata itu di kantornya di Ambeua. ”Menjadi daya tarik sekaligus tantangan pariwisata di sini”, lanjutnya. Saya penasaran dengan kalimat yang baru saja terucap.
“Masyarakat Kaledupa relatif belum terbiasa melihat hal-hal baru. Contoh sederhana, pakaian. Jangankan turis luar yang biasa buka-bukaan, pelancong lokal yang bajunya sedikit terbuka saja bisa dipelototi,” jelas La Bloro. “Pernah ada sepasang turis asing yang diminta pergi oleh sekelompok warga karena pakaian mereka dianggap mengganggu.” Gelora pariwisata rupanya menimbulkan benturan sosial.
“Tapi mungkin hanya masalah waktu. Lihat saja Bali dan Yogyakarta”. La Bloro menghisap rokoknya dalam-dalam. “Sekarang yang penting darat juga harus diurus. Laut itu musiman dan hanya yang berduit saja yang bisa berperan. Satu lagi, menghubungkan antar destinasi. Sekarang kan belum banyak tersambung”.





Baca juga : Museum Multatuli, Dari Lebak Untuk Dunia
Menurutnya Forkani tengah merintis yang disebut Kaledupa Walking Tour, semacam paket wisata yang pesertanya berkunjung ke beberapa titik di Pulau Kaledupa dan turut melakukan aktifitas yang biasa dilakukan warga sekitar. Contoh di Desa Pajam, pengunjung ikut menenun dan memasak makanan lokal. Harapannya pengunjung tak sekedar mengambil foto lalu pamer di sosial media.”Kami coba jual pengalaman dan idealnya itulah wisata budaya. Esensi tradisi itu kan kebiasaan sehari-hari, bukan cuma melihat tari atau upacara,” jelasnya. ”Ini sekaligus upaya menarik turis asing yang banyak beredar di Hoga.”
Hoga dan Bajo Sampela
Pulau kecil berjarak sekitar 20 menit penyebrangan itu adalah pusat pusaran wisata Kaledupa. Penggerak utamanya adalah Operation Wallacea. Organisasi riset maritim asal Inggris itu memiliki program semacam summercamp bagi pelajar luar negeri yang menekuni ilmu kelautan. Selama liburan musim panas sekitar Agustus, Hoga dipenuhi bule yang menyelam bukan sekedar rekreasi namun juga belajar. Saya melihat beberapa bangunan kayu sederhana menyerupai kelas dan di dalamnya para pelajar itu bergantian mempresentasikan apa yang mereka dapat saat berada di bawah laut. Ironi dan iri menyeruak kala melihatnya. Indonesia perlu mencontoh.
Destinasi lainnya yaitu Sampela, kampung di tengah laut yang dihuni Suku Bajo. Sepuluh menit menyebrang dari Hoga, saya melihat modernitas menjamah suku yang selama ini banyak dicitrakan dengan kehidupan laut yang tradisional. Parabola dimana-mana, gawai tergenggam erat di tangan para warga dan tentu saja interaksi dengan banyak pengunjung bule yang tinggal di Hoga. Bahkan Sampela seolah membangun sendiri daratannya dengan batu dan semen di bagian tengah. Hanya rumah-rumah sisi luar saja yang benar-benar menancap ke dasar laut dangkal. Bajo memang bagian jualan utama pariwisata Wakatobi. Ada banyak perkampungan Bajo di Wakatobi. Sampela salah satu yang populer apalagi sejak sebuah film dengan artis ibukota mengambil lokasi syuting di sini 2011 lalu.




Baca Juga: Sejumput Kisah Negeri Daun Emas
Wangi-Wangi, Pintu Gerbang Wakatobi
“Anak-anak muda di sini banyak yang hijrah, bang. Ke Bau-Bau, Kendari atau Makassar yang lebih metropolitan. Tanah di sini tidak menjanjikan apalagi untuk ukuran era modern,” kesah Anan. Menurutnya perikanan dan pariwisata yang jadi andalan sedang lesu. “Sulit kalau mengandalkan laut saja. Tempat-tempat selam lain makin banyak. Persaingan keras, bang.”
Pagi itu saya dijemput Anan di Pelabuhan Jabal usai menyebrang dari Kaledupa ke Wangi-Wangi. Di dalam mobil ia banyak bercerita tentang tanah kelahirannya ini. “Kalau berkunjung tahun 80-90an jangan kaget lihat motor Ducatti berkeliaran. Banyak barang bajakan dan curian beredar di sini” tukasnya. Rupanya dulu pernah ada kapal dari Wangi-Wangi ke Singapura. “Tapi sekarang sudah hampir tidak ada sejak Wakatobi jadi kabupaten baru apalagi Wangi-Wangi jadi ibukota.” Saya menanyakan asal mula Wangi-Wangi yang tak terduga itu. Anan hanya mengangkat bahunya.
Usai menaruh barang di hotel, saya segera menarik tuas gas roda dua menjelajah pulau yang sempat dijuluki tanah perompak ini. Pembangunan jalan rupanya tengah marak, mengingatkan pada obrolan beberapa hari lalu dengan sesama tamu homestay yang seorang pegawai Kementrian Pekerjaan Umum. Ia berkata bahwa Wakatobi termasuk salah satu daerah yang mendapat hibah dana pemerintah pusat melalui instansinya untuk pembangunan akses jalan. Itu berkat status destinasi wisata prioritas yang diberikan pemerintah pusat. Label itu sudah menuai hasil rupanya.
Menyapa Liya
Berjarak 10 km dari pusat keramaian di Wanci, saya tiba di Desa Liya Togo yang diyakini desa tertua di Wangi-Wangi. Di sini sebagian besar tempat tinggal warga berupa rumah panggung. Desa ini berbentuk perkampungan yang terzonasi dengan pusatnya satu area berisi empat bangunan utama; masjid, benteng, makam, dan baruga atau rumah tempat rapat adat. Keempatnya mengelilingi sebuah lapangan seukuran setengah lapangan bola. Di sinilah berlangsung Posepa’a yaitu adu kaki atau saling tendang sesama warga yang dilakukan secara berpasangan. Tradisi ini biasa dilakukan usai Solat Id dan selalu ramai pengunjung.
Masjid Raya Liya Togo yang berada di sisi barat, menurut prasasti di depannya dibangun pada abad ke 16 alias yang tertua di Wakatobi. Namun fasad bangunan ibadah tersebut nampak tak seperti bangunan berusia lima abad. Sangat mungkin beberapa kali renovasi mengubah keaslian bentuknya. Barangkali yang lebih orisinil adalah Benteng Liya Togo yang berwujud susunan batu karang seperti lazimnya benteng di Wakatobi.




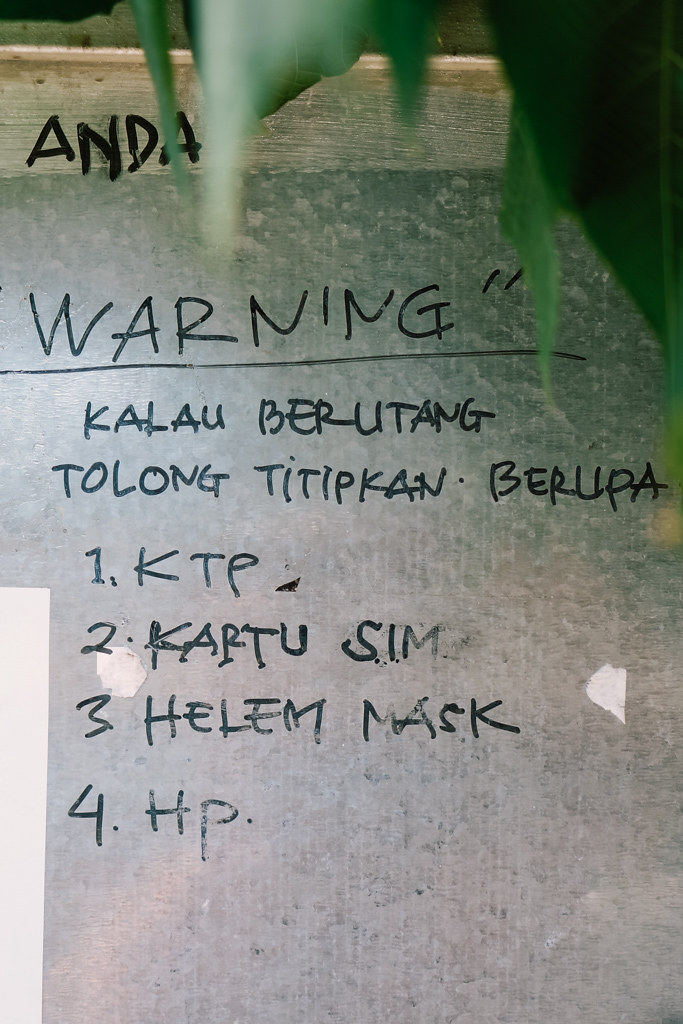


Tata ruang Liya Togo terbilang rapi untuk ukuran desa tua dan sepertinya tepat dikemas sebagai wisata minat khusus terutama sejarah dan arsitektur. Desa ini sesungguhnya cukup kondang di lingkup turisme lokal. Belakangan saya tahu warga setempat telah membentuk kelompok sadar wisata. Liya Togo adalah salah satu contoh merekahnya desa wisata di Wakatobi. Dampaknya, meski menyelam masih jadi sajian utama, obyek-obyek baru seperti benteng, gua, pemandian alam, desa tenun, mercusuar dan lain-lain bermunculan dan turut mewarnai pariwisata lokal.
Geliat wisata non selam sebenarnya terasa beberapa tahun terakhir saat berbagai festival berbasis budaya lokal mulai rutin digelar dan tiap pulau setidaknya memiliki satu agenda unggulan. Binongko mempunyai Festival Pandai Besi, Tomia dengan Festival Pulau Tomia, dan Kaledupa memiliki Festival Barata Kaledupa. Wangi-Wangi sendiri menggelar hajatan nasional Wakatobi Wave yang masih dominan tema bawah laut namun konten tradisi dan budaya mulai banyak mengambil porsi.
Bumerang Bernama Destinasi Digital
Wakatobi sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Namun atensi tersebut hendaknya dicurahkan secara berimbang. Seperti yang dituturkan seorang turis Jakarta yang duduk di sebelah saat saya terbang pulang. “Semoga yang non fisik juga dijamah. Saya khawatir yang fisik justru berlebihan hanya karena kasat mata.” Ia mendengar gosip akan dibangun beberapa selfie spot di Wakatobi dan jika benar ia termasuk yang kontra.
“Uang mengalir cepat namun menguap tak kalah sigap. Selfie spot membuat pengunjung sebatas berburu foto demi eksis di dunia maya tapi melupakan pengalaman dan hal-hal baru yang menjadi esensi berwisata,” serunya. ”Destinasi digital tanpa diimbangi konten yang bercerita ibarat buah berkulit mulus tapi berdaging busuk”. Sebuah peringatan bagi para pemangku kepentingan.
Sebuah Lecutan
Peristiwa terakhir bisa juga menjadi duri bagi pengembangan wisata Wakatobi. Seekor ikan Paus terdampar dalam kondisi mati di Pulau Kapota tetangga Wangi-Wangi pada November 2018. Sorotan utamanya ada di isi perut si paus malang itu, 5,9 kilogram sampah sebagian besar plastik. Saat tulisan ini dibuat masih belum ada kepastian penyebab kematian namun praduga langsung tertuju ke benda-benda yang tak seharusnya berada di dalam perut si ikan. Sangkaan tentu terlempar pada perilaku tak bertanggung jawab orang-orang di Wakatobi baik warga maupun bukan meskipun asal sampah tersebut belum dipastikan. Terlepas masih diselidikinya kasus tersebut, perisitiwa ini ibarat lecutan yang menyakitkan namun mampu membuat kuda berlari kencang, harusnya.
Sebulan lebih beranjangsana, saya merasa Wakatobi sudah berada di trek yang benar dalam bidang pariwisata namun masih berjalan pelan. Selain akses, tantangan terbesar yang harus cepat diselesaikan adalah koneksi, kolaborasi, SDM dan membangun kesadaran lingkungan. Harus diakui citra pariwisata Wakatobi tengah surut. Perlu langkah kreatif untuk mengatasinya. Jawabannya mungkin ada di batuan bertanah penghampar sekian pesona baru yang menunggu untuk dipoles dan dilirik. Saat itu terjadi, saya yakin Wakatobi memang layak berada di kotak kanan bawah papan monopoli.



Foto kerumunan orang yang nonton itu epic banget mas 😀
hahah…nganti munggah wit